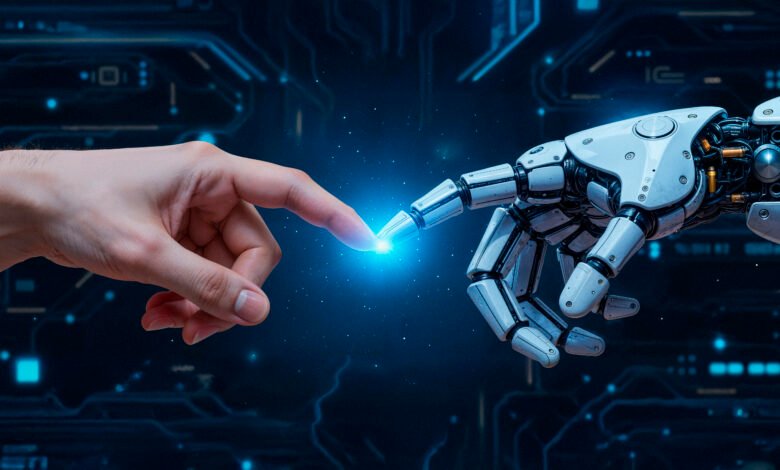
Kolom Muhammadiyah Jabar—
Ledakan kecerdasan buatan dalam beberapa tahun terakhir tidak hanya mengubah cara manusia bekerja, tetapi juga cara manusia berpikir. Kita kini menyaksikan tulisan lahir dengan kecepatan yang belum pernah ada sebelumnya—rapi, logis, sopan, dan sekilas tampak cerdas. Namun di balik kemudahan itu, tersembunyi sebuah paradoks besar: semakin cepat tulisan diproduksi, semakin dangkal proses berpikir yang melahirkannya.
Sebuah video narasi di kanal YouTube GadgetIn tentang industri AI memperlihatkan sisi lain dari revolusi ini. Pada menit 01:09, dijelaskan bahwa layanan AI seperti ChatGPT dan Gemini membutuhkan daya komputasi yang sangat besar, sehingga pusat data menjelma menjadi jantung ekonomi baru. Dampaknya bukan sekadar teknis, melainkan struktural. Produsen memori raksasa seperti Samsung, Micron, dan SK Hynix mulai mengalihkan fokus produksi mereka ke pasar AI karena sektor ini berani membayar jauh lebih mahal dibandingkan pasar konsumen biasa. Bahkan Micron mengambil langkah ekstrem dengan menghentikan merek memori konsumennya, Crucial, demi berkonsentrasi penuh pada kebutuhan industri AI (menit 03:07).
Fenomena ini menunjukkan bahwa pergeseran ke AI bukan hanya persoalan ekonomi. Dunia industri sedang berlari kencang menuju kecerdasan buatan, dan manusia—sadar atau tidak—ikut terseret di dalamnya. Masalah muncul ketika laju teknologi melampaui kemampuan intelektual manusia untuk mengimbanginya.
Menulis, pada hakikatnya, bukan sekadar menghasilkan teks. Ia adalah proses berpikir: perjalanan dari kekacauan ide menuju keteraturan argumen, dari kebingungan menuju kejelasan. Proses ini melatih otak untuk menganalisis, menyusun logika, dan mempertanyakan asumsi. Namun kehadiran AI secara perlahan mengubah peran manusia, dari kreator menjadi operator, dari penulis menjadi sekadar pemberi instruksi—prompt engineer.
Kini manusia tidak lagi membangun gagasan dari nol. Cukup menentukan hasil akhir yang diinginkan, lalu mesin menyusun sisanya. Tahap inkubasi ide—fase paling krusial dalam kreativitas—perlahan menghilang. Kita tidak lagi membangun bangunan pemikiran, melainkan memilih bangunan prefabrikasi yang telah disediakan AI. Inilah bentuk awal erosi intelektual yang sering kali luput disadari.
Laporan Stanford Human-Centered Artificial Intelligence (2024) menyebut fenomena ini sebagai semantic flattening. Karena AI bekerja berdasarkan probabilitas kemunculan kata yang paling umum, ia menghasilkan tulisan yang aman, netral, dan minim risiko. Tragisnya, tulisan manusia yang hebat justru sering lahir dari kegelisahan, keberanian memilih diksi, bahkan dari ketidaksempurnaan logika yang artistik. Demi kerapian, AI menghapus semua itu. Akibatnya, gaya komunikasi manusia perlahan menjadi seragam, datar, dan kehilangan daya hidup.
Dampak ini semakin terasa di dunia pendidikan. Penelitian dalam Journal of Educational Psychology (2024) mencatat penurunan kemampuan argumen struktural hingga 27% pada mahasiswa yang terbiasa menggunakan AI untuk menulis esai. Kemampuan berargumen sejatinya adalah otot mental. Jika otot tersebut terus-menerus digantikan oleh “kursi roda” bernama AI, maka yang terjadi bukan efisiensi, melainkan atrofi. Generasi baru berisiko kehilangan kemampuan mempertahankan pendapat dalam diskusi nyata, karena mereka tidak pernah belajar menyusun logika dari awal.
Lebih mengkhawatirkan lagi adalah munculnya ilusi kepintaran. Penggunaan AI menciptakan bias kognitif ketika seseorang merasa telah memahami suatu topik hanya karena ia mampu meminta AI menjelaskannya dengan baik. Padahal, pengetahuan itu tidak benar-benar “menempel” di otak. Fenomena ini dikenal sebagai cognitive offloading—beban berpikir dipindahkan ke mesin, sementara manusia kehilangan nutrisi intelektual dari proses berpikir itu sendiri.
Pada titik inilah AI berpotensi menjadi “penjara intelektual” baru. Bukan karena algoritmanya jahat, melainkan karena standar baru yang ia ciptakan. Kita mulai hidup dalam budaya instan, di mana tulisan yang lambat dan penuh refleksi dianggap tidak efisien. Tulisan yang unik, sedikit kacau, dan penuh pergulatan ide—tanda manusia sedang benar-benar berpikir—mulai dianggap salah karena tidak mengikuti pola AI yang selalu rapi dan elegan.
Padahal, kerapian bukanlah ukuran kedalaman. Keberanian intelektual justru sering lahir dari ketidakteraturan. Ketika manusia mulai meniru gaya AI yang seragam, kita perlahan kehilangan keberagaman cara berpikir.
Masalahnya bukan pada AI itu sendiri. Teknologi pada dasarnya netral. Tragedi intelektual muncul ketika manusia lebih memilih kenyamanan daripada proses berpikir, ketika kecepatan lebih dihargai daripada kedalaman, dan efisiensi dianggap lebih penting daripada orisinalitas. Ironisnya, di saat mesin semakin cerdas, manusia justru semakin malas berpikir.
AI seharusnya menjadi alat bantu, bukan pengganti. Ia dapat mempercepat kerja mekanis, tetapi fondasi ide, kerangka logika, dan keberanian berpendapat harus tetap lahir dari manusia. Orisinalitas tidak bisa diproduksi mesin; ia tumbuh dari pengalaman, konflik batin, dan refleksi pribadi.
Pada akhirnya, tragedi intelektual abad digital bukan karena AI terlalu pintar, melainkan karena manusia terlalu cepat menyerah. Jika manusia berhenti berpikir, maka ribuan tulisan hanya akan menjadi arsip rapi tanpa jiwa. Abad digital seharusnya menjadi era pembebasan kreativitas, bukan kepunahan intelektual.
Dan tragedi sejati bukan ketika mesin mampu menulis seperti manusia, melainkan ketika manusia tak lagi mau berpikir seperti manusia.
⸻
Referensi
1. Cognitive Offloading and Generative AI in Writing Processes — University of Pennsylvania (2023).
2. Semantic Flattening in AI-Generated Content — Stanford Human-Centered Artificial Intelligence Report (2024).
3. AI-Assisted Writing and Decline in Argumentation Skills Among Students — Journal of Educational Psychology (2024).
4. AI’s Role in Digital Content Explosion — IBM Global AI Adoption Index (2024).
5. Carr, N. (2010). The Shallows: What the Internet Is Doing to Our Brains.
6. Kahneman, D. (2011). Thinking, Fast and Slow.
Penulis : Sayid Damar Wicaksono (Sekretaris PCPM Pondok Gede)








